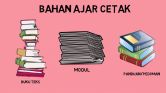Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Unesa
| Program Studi | : | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
| Koordinator Program Studi | : | FERA RATYANINGRUM |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pembelajaran seni rupa berbasis creativepreneur dengan modal budaya visual nusantara.
- Menghasilkan lulusan penelitian dasar maupun terapan di bidang pendidikan berbasis budaya visual nusantara dengan pendekatan creativepreneur.
- Menghasilkan lulusan yang responsif terhadap perubahan masyarakat melalui kegiatan kesenirupaan yang inovatif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Visi
Mengembangkan ilmu pendidikan seni rupa yang unggul, adaptif, dan inovatif berbasis creativepreneur dan modal budaya visual nusantaraMisi
- Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang seni rupa yang berbasis creativepreneur dan modal budaya visual nusantara.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan seni rupa berbasis creativepreneur dan modal budaya visual nusantara.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi berbasis creativepreneur dan modal budaya visual nusantara untuk pengembangan produktivitas masyarakat.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Seni Rupa 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
8821003051
GAMBAR BENTUK
3.00
8821003060
GAMBAR PROYEKSI PERSPEKTIF
3.00
8821002085
KONSEP PENDIDIKAN SENI
2.00
8821003062
GAMBAR RAGAM HIAS
3.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8821003152
RUPA DASAR 2 D
3.00
8821002155
SEJARAH SENI RUPA BARAT
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8821003190
SKETSA
3.00
8821002207
TEORI BELAJAR
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000002005
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
2.00
8821003153
RUPA DASAR 3 D
3.00
8821002296
SEJARAH SENI RUPA ASIA DAN INDONESIA
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8821002289
FILSAFAT SENI
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
8821002204
TELAAH KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8821002209
TINJAUAN SENI RUPA
2.00
8821002297
BUDAYA RUPA NUSANTARA
2.00
8821003057
GAMBAR MODEL
3.00
8821002292
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
8821002140
PERENC.PEMBELAJARAN SENI
2.00
8821005290
SENI RUPA 2 DIMENSI
3.00
8821005291
SENI RUPA 3 DIMENSI
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8821002294
KETRAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MICRO
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
8821003091
KRIYA KAYU
3.00
8821003096
KRIYA KERAMIK
3.00
8821003116
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
8821002295
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
2.00
8821002300
PENDIDIKAN SENI INKLUSI
2.00
8821003012
AUDIO VISUAL
3.00
8821003026
DESAIN GRAFIS
3.00
8821002275
EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
2.00
8821003101
KRIYA LOGAM
3.00
8821003106
KRIYA TEKSTIL
3.00
8821003169
SENI LUKIS
3.00
8821002192
STATISTIKA
2.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (2 SKS)
- Paket Matakuliah Bela Negara (4 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (4 SKS)
- Paket Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (4 SKS)
- Paket Matakuliah Pertukaran Mahasiswa (2 SKS)
- Paket Matakuliah Proyek Kemanusiaan (4 SKS)
- Paket Matakuliah Riset (4 SKS)
- Paket Matakuliah Studi Independen (4 SKS)
- Paket Matakuliah Wirausaha (4 SKS)
Matakuliah Asistensi Mengajar
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020171
PERENCANAAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR
2.00
Matakuliah Bela Negara
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020169
PERENCANAAN PROGRAM BELA NEGARA
2.00
1000020148
EVALUASI PROGRAM BELA NEGARA
2.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020108
EVALUASI PROGRAM MAGANG PRAKTIK INDUSTRI
2.00
1000020174
PERENCANAAN PROGRAM MAGANG
2.00
Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020175
EVALUASI PROGRAM PROYEK DI DESA
2.00
1000020168
PERENCANAAN PROGRAM PROYEK DI DESA
2.00
Matakuliah Pertukaran Mahasiswa
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020170
PERENCANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
2.00
Matakuliah Proyek Kemanusiaan
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020118
EVALUASI PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
2.00
1000020166
PERENCANAAN PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
2.00
Matakuliah Riset
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020133
EVALUASI PROGRAM PENELITIAN DAN RISET
2.00
1000020172
PERENCANAAN PROGRAM RISET
2.00
Matakuliah Studi Independen
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020123
EVALUASI PROGRAM STUDI DAN PROYEK INDEPENDEN
2.00
1000020173
PERENCANAAN PROGRAM STUDI INDEPENDEN
2.00
Matakuliah Wirausaha
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020167
PERENCANAAN PROGRAM WIRAUSAHA
2.00
1000020128
EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8821003364
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP)
3.00
8821004365
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP)
4.00
8821003366
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN MENGGAMBAR (MBKM-PLP)
3.00
8821003363
PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP)
3.00
MBKM0031
PLP EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0032
PLP PERENCANAAN PROGRAM
2.00
8821003367
PRESENTASI KARYA SENI RUPA SISWA (MBKM-PLP)
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8821003005
ANIMASI
3.00
8821002110
MANAJEMEN SENI
2.00
8821004128
PENDALAMAN SENI LUKIS
4.00
8821002299
PENGETAHUAN HKI
2.00
8821003211
TIPOGRAFI
3.00
8821003227
CENDERAMATA **
3.00
8821003178
ILUSTRASI BUKU DAN KOMIK **
3.00
8821004121
PENDALAMAN DESAIN GRAFIS
4.00
8821004224
PENDALAMAN SENI KRIYA (KAYU)
4.00
8821004226
PENDALAMAN SENI KRIYA (KERAMIK)
4.00
8821004223
PENDALAMAN SENI KRIYA (LOGAM)
4.00
8821004301
PENDALAMAN SENI KRIYA (TEKSTIL)*
4.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
8821003372
DIGITAL MARKETING**
3.00
8821003373
PERSONAL BRANDING**
3.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 8821003051 | GAMBAR BENTUK | 3.00 | |
| 8821003060 | GAMBAR PROYEKSI PERSPEKTIF | 3.00 | |
| 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2.00 | |
| 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 3.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 3.00 | |
| 8821002155 | SEJARAH SENI RUPA BARAT | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 8821003190 | SKETSA | 3.00 | |
| 8821002207 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 1000002005 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 8821003153 | RUPA DASAR 3 D | 3.00 | |
| 8821002296 | SEJARAH SENI RUPA ASIA DAN INDONESIA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8821002289 | FILSAFAT SENI | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 8821002204 | TELAAH KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
| 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2.00 | |
| 8821002297 | BUDAYA RUPA NUSANTARA | 2.00 | |
| 8821003057 | GAMBAR MODEL | 3.00 | |
| 8821002292 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
| 8821002140 | PERENC.PEMBELAJARAN SENI | 2.00 | |
| 8821005290 | SENI RUPA 2 DIMENSI | 3.00 | |
| 8821005291 | SENI RUPA 3 DIMENSI | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8821002294 | KETRAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MICRO | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8821003091 | KRIYA KAYU | 3.00 | |
| 8821003096 | KRIYA KERAMIK | 3.00 | |
| 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
| 8821002295 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8821002300 | PENDIDIKAN SENI INKLUSI | 2.00 | |
| 8821003012 | AUDIO VISUAL | 3.00 | |
| 8821003026 | DESAIN GRAFIS | 3.00 | |
| 8821002275 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8821003101 | KRIYA LOGAM | 3.00 | |
| 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 3.00 | |
| 8821003169 | SENI LUKIS | 3.00 | |
| 8821002192 | STATISTIKA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020171 | PERENCANAAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020169 | PERENCANAAN PROGRAM BELA NEGARA | 2.00 | |
| 1000020148 | EVALUASI PROGRAM BELA NEGARA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020108 | EVALUASI PROGRAM MAGANG PRAKTIK INDUSTRI | 2.00 | |
| 1000020174 | PERENCANAAN PROGRAM MAGANG | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020175 | EVALUASI PROGRAM PROYEK DI DESA | 2.00 | |
| 1000020168 | PERENCANAAN PROGRAM PROYEK DI DESA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020170 | PERENCANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020118 | EVALUASI PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN | 2.00 | |
| 1000020166 | PERENCANAAN PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020133 | EVALUASI PROGRAM PENELITIAN DAN RISET | 2.00 | |
| 1000020172 | PERENCANAAN PROGRAM RISET | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020123 | EVALUASI PROGRAM STUDI DAN PROYEK INDEPENDEN | 2.00 | |
| 1000020173 | PERENCANAAN PROGRAM STUDI INDEPENDEN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020167 | PERENCANAAN PROGRAM WIRAUSAHA | 2.00 | |
| 1000020128 | EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8821003364 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP) | 3.00 | |
| 8821004365 | IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP) | 4.00 | |
| 8821003366 | PENGEMBANGAN KETRAMPILAN MENGGAMBAR (MBKM-PLP) | 3.00 | |
| 8821003363 | PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SENI RUPA (MBKM-PLP) | 3.00 | |
| MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0032 | PLP PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| 8821003367 | PRESENTASI KARYA SENI RUPA SISWA (MBKM-PLP) | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8821003005 | ANIMASI | 3.00 | |
| 8821002110 | MANAJEMEN SENI | 2.00 | |
| 8821004128 | PENDALAMAN SENI LUKIS | 4.00 | |
| 8821002299 | PENGETAHUAN HKI | 2.00 | |
| 8821003211 | TIPOGRAFI | 3.00 | |
| 8821003227 | CENDERAMATA ** | 3.00 | |
| 8821003178 | ILUSTRASI BUKU DAN KOMIK ** | 3.00 | |
| 8821004121 | PENDALAMAN DESAIN GRAFIS | 4.00 | |
| 8821004224 | PENDALAMAN SENI KRIYA (KAYU) | 4.00 | |
| 8821004226 | PENDALAMAN SENI KRIYA (KERAMIK) | 4.00 | |
| 8821004223 | PENDALAMAN SENI KRIYA (LOGAM) | 4.00 | |
| 8821004301 | PENDALAMAN SENI KRIYA (TEKSTIL)* | 4.00 | |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 | |
| 8821003372 | DIGITAL MARKETING** | 3.00 | |
| 8821003373 | PERSONAL BRANDING** | 3.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi Kurikulum
Berdasarkan adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Unesa menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Perumusan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka dengan mengusung tema “Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Kampus Merdeka”, diperoleh tiga pilar dalam kampus merdeka sesuai dengan pesan kunci Mendikbud. Pilar 1, dosen adalah penggerak, harus profesional dan inovatif. Pilar 2, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Pilar 3, konsolidasi kebijakan. dimana kampus merdeka memiliki 4 kebijakan utama, yaitu pembukaan prodi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, serta hak belajar tiga semester di luar program studi. Sehingga unesa mengadakan program magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independent, serta proyek kemanusiaan. “Pengembangan kurikulum merdeka belajar ini tidak hanya mengedukasi dosen, tapi mahasiswa juga perlu tau, agar dapat dipersiapkan dari awal. Sehingga kurikulum merdeka belajar program studi Pendidikan Seni Rupa dirancang untuk memberikan kemerdekaan mahasiswa pada semester lima untuk memilihn progra perkuliahan. prinsip merdeka belajar ini sangat bagus karena bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar prodi dan capaian pembelajaran. Kurikulum merdeka belajar yang rencananya akan diterapkan pada semester gasal 2020/2021 ini akan diberlakukan pada mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Mengusung model 512 serta pola perkuliahan 4121 atau 42a12b1. Nantinya akan dilakukan kompres, penghilangan mata kuliah yang tidak relevan, penggabungan mata kuliah yang bergayut, pengurangan bobot sks mata kuliah, penambahan total sks lulusan (144-150), pemunculan mata kuliah baru, dan lain sebagainya.
Tracer Study
Alumni Pendidikan Seni Rupa yang sudah mengisi sebanyak 71.67%, sedangkan yang masih dalam proses mengisi 3.33%, dan yang belum mengisi sebanyak 25.00%. Persentase alumni yang sudah mengisi tracer study cukup tinggi dibandingkan dengan alumni yang belum mengisi dan yang masih tahap pengisian. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran alumni Pendidikan Seni Rupa terhadap pengisian survey tracer study sudah cukup baik, sehingga memudahkan dalam pengabilan kesimpulan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan pada hasil survey, diketahui bahwasannya metode pembelajaran yang dianggap responden paling bermanfaat serta berperan dalam kehidupan karier mereka saat ini adalah Metode Diskusi. Metode diskusi mendapatkan nilai rerata tertinggi yaitu 4.4, sedangkan nilai terendah ada pada Metode Partisipasi dalam Proyek Riset yang mendapatkan nilai rerata 3.53. Dimasa yang akan datang, hendaknya metode-metode pembelajaran yang dinilai kurang memiliki peranan dalam masa depan alumni dapat ditinjau ulang dan dioptimalkan, sehingga alumni Jurusan Seni Rupa FBS dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Adapun 3 metode yang mendapatkan rerata terendah adalah Metode Magang, Metode Demostrasi, dan Metode Partisipai dalam Proyek Riset.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
| Sejarah Seni Rupa Barat | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| FILSAFAT SENI | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Skripsi | 6 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Rupa Dasar 2 D | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Manajemen Seni | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Kuliah Kerja Nyata | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Seni Rupa 2 Dimensi | 3 | 55.56% | 44.44% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Kriya (Batik) | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Kriya (Logam) | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Bahasa Inggris | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Desain Grafis | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Animasi | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Gambar Bentuk | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Gambar Model | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kriya Tekstil | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
| Kriya Keramik | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Gambar Ragam Hias | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Audio Visual | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Konsep Pendidikan Seni | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Telaah Kurikulum Sekolah | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Kriya (Keramik) | 4 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||
| Gambar Proyeksi Perspektif | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kewirausahaan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Cenderamata ** | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Murni (Lukis) | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Tinjauan Seni Rupa | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kriya Kayu | 3 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
| Teori Belajar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kriya Logam | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Seni Lukis | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Desain Grafis | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Sketsa | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Statistika | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Tipografi | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Ilustrasi Buku dan Komik ** | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Kriya (Tekstil)* | 4 | 62.5% | 25% | 12.5% | 100 % | ||||||
| Pengetahuan HKI | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Seni Rupa 3 Dimensi | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Perencanaan Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Multimedia Pembelajaran | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Budaya Rupa Nusantara | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendidikan Seni Inklusi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Rupa Dasar 3 D | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Metodologi Penelitian | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Desain Grafis II * | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Aplikasi Komputer | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Fotografi | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Tipografi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kriya Anyam | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Kriya Kayu II * | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
| Pendalaman Seni Lukis | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Seni Patung Dasar | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Seni Lukis Dasar | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| E S T E T I K A | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pembelajaran Inovatif | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Kriya (Kayu) | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Tugas Akhir (Ta)/skripsi | 6 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Perenc.pembelajaran Seni | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Desain Web ** | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Pendalaman Seni Murni (Seni Media Baru)* | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Cinderamata | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Analisis Kebutuhan Asistensi Mengajar (MBKM) | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa
Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY VALUE
Pengembangan kurikulum di Unesa juga secara khusus turut mewujudkan visi dan misi Unesa yakni unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan, maka setiap prinsip tersebut harus mengarah pada visi dan misi tersebut. Secara umum prinsip pengembangan kurikulum Unesa adalah:
A. Relevansi
Kurikulum yang dikembangkan harus memiliki keterkaitan antara bidang ilmu (diciplin/content) dengan kebutuhan masyarakat (social needs) sebagai pengguna lulusan. Keterkaitan yang dimaksudkan bahwa kurikulum dikembangkan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pengguna/pasar melainkan juga merupakan implementasi dari kajian mendalam dari bidang ilmu yang dikembangkan.
B. Fleksibilitas
Kurikulum yang dikembangkan memiliki keluwesan terhadap implementasi di lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah implementasi kurikulum tersebut dalam pembelajaran atau hasil kurikulum tersebut di dunia kerja yang diimplementasikan oleh para lulusan kurikulum tersebut.
C. Kontinuitas
Kurikulum yang dikembangkan memiliki prinsip kontinuitas (berkesinambungan) antar
bagian disiplin ilmu sebagai content. Hal ini diperlukan agar kurikulum tidak terkesan terputus antar bagian atau merupakan lingkaran yang berpusat di satu tempat saja.
D. Efisiensi
Kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan aspek meritokrasi untuk memperoleh daya guna dalam sistem secara keseluruhan. Efisiensi diperoleh melalui pemanfaatan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya lain untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan.
E. Keefektifan
Kurikulum yang dikembangkan perlu mencermati tujuan secara sungguh-sungguh dalam upaya pencapaiannya dengan memafaatkan/mengelola proses dan sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan.
Elemen-elemen kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum program studi memuat (1) afeksi, (2) karakter, (3) keterampilan berpikir tingkat tinggi, (4) kemampuan tertentu yang relevan dengan kebutuhan individu, kelompok, masyarakat luar, dan (5) peluang untuk pengembangan diri. Afeksi yang ditumbuh-kembangkan pada mahasiswa Unesa, sesuai dengan landasan kepribadian dan sikap perilaku berkarya di dalam Perpres nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI, yakni:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
LANDASAN FILOSOFIS
Karakter yang ditumbuh-kembangkan pada mahasiswa Unesa, sesuai dengan moto growing with character, meliputi: Iman, Cerdas, Mandiri, Jujur, Peduli, dan Tangguh (dengan akronim: “Idaman Jelita”). Penguatan Pendidikan Karakter menjadi wajib menyertai Merdeka Melajar menekankan enam karakter yang harus menjadi dasar pembelajaran; 1) computational thinking, 2) Creative, 3) Ctitical thinking, 4) Collaboration, 5) Communication, dan 6) Compassion.
Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976). Perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.
Berkaitan dengan masalah tersebut di atas ada baiknya kita mencoba menengok kembali filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Tiga prinsip yang disebut “Trikon”, y.i. Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia. Kesemuanya itu dapat dicapai jika konsep sistem “among” yang berjiwa kekeluargaan dalam pendidikan bersendikan atas dua dasar, yaitu pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya; kedua kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi kekuatan lahir dan batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya. Prinsip yang dikemukakan ini sejalan dengan karakter yang diharapkan mengejahwantah sebagai sikap pendidik dan pemimpin yaitu: Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, dan Tut wuri handayani.
Sasaran utama dari pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran adalah optimalisasi potensi manusia. Paulo Freire, seorang tokoh Demokrasi Pendidikan memandang bahwa manusia itu berproses, yang berarti manusia tersebut belum selesai (belum utuh). Kemudian bagaimana membentuk manusia yang utuh?. Manusia yang diinginkan adalah manusia yang otonom terhadap dirinya, terbebas dari tekanan dan memiliki dasar hidup yang jelas dan realitas. Di sisi lain, dalam pandangan Freire, humanisasi adalah sebuah gambaran manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia tersebut memproleh keutuhan. Keutuhan yang diperoleh menjadi manusia yang ideal (humanisasi) ini membutuhkan manusia yang sadar diri. Adanya kesadaran dalam diri manusia itu diperoleh dengan kebebasan (Freire, 2001).
Impelemtasi Merdeka Belajar (Nadiem, 2019) sejalan dengan filosofi Demokrasi Pendidikan (Freire, 2001). Di dalam aktivitasnya terlibat interaksi antara peserta didik dengan sejumlah sumber belajar. Dosen sebagai pendidik sekaligus berperan sebagai salah satu sumber belajar dan mahasiswa sebagai peserta didik, secara hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis “untuk menjadi” (on becoming). Dosen sebagai salah satu sumber belajar artinya masih banyak sumber belajar lain yang dapat dipilih oleh mahasiswa dan konsekwensinya dosen memiliki kewajiban untuk memberi keleluasaan pada mahasiswa dalam menentukan pilihan sumber lain maupun cara dan tempat belajarnya yang sesuai dengan minatnya. Hal ini ditegaskan oleh Freire bahwa “The purpose of adult education is to help them to learn, not to teach them all you know and thus stop them from learning”.
Asumsi filosofis yang perlu dikembangkan dalam konteks ini bahwa pembelajaran adalah proses berfikir untuk mencari dan menemukan (bukan diajari). Implementasinya proses pembelajaran diarahkan pada;
- Pembentukan keterampilan mental tertentu (Teaching of thinking) seperti keterampilan berfikir kritis, berfikir kreatif.
- Usaha menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong terhadap pengembangan kognitif, seperti menciptakan suasana keterbukaan yang demokratis, menciptakan iklim yang menyenangkan (teaching for thinking).
- Upaya untuk membantu agar peserta didik lebih sadar terhadap proses berfikirnya (teaching about thinking). Maka dari itu, akal dan kecerdasan peserta didik harus dikembangkan dengan baik. Karena Lembaga pendidikan bukan berfungsi untuk memindahkanan pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga berfungsi sebagai pemindahan nilai (transfer of value), sehingga peserta didik menjadi terampil, berintelektual baik, dan memiliki internalisasi nilai dalam wujud karakter. Mereka harus diberi kemerdekaan untuk berbuat sesuai dengan cara dan kemampuannya masing-masing dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan daya kreativitasnya yang didasari oleh sikap nilai yang standar.
LANDASAN SOSIOLOGIS
Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi.
Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.
Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration) (Caliguri, 2012)2. Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “Tri- Kon
Penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan berbasis pada kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa dengan didasari oleh: (a) integrasi kearifan lokal budaya yang bersumber dari core value hormat, rukun, dan tolong menolong sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter, (b) untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik, pembelajaran dilakukan dengan belajar sambil berbuat, belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui perlibatan sosial, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial- kultural, (c) Implementasi model pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum kampus merdeka dilakukan dengan pendekatan pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi nilai.
LANDASAN HISTORIS
Secara historis pengembangan kurikulum di Unesa berjalan searah dengan pengembangan lembaga yang diawali dari kursus guru B-I dan B-II pada tahun 1950an, yang selanjutnya berkembang menjadi Akademi Pendidikan Guru hingga FKIP dan IKIP Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas sebagai perluasan mandat untuk mengembangkan program nonkependidikan disamping program kependidikan yang telah lama dilakukan. Dengan demikian pengembangan kurikulum dilakukan pula mengikuti proses tersebut seiring dengan peraturan dan perundangan yang berlaku saat itu.
Kurikulum di Unesa mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Perkembangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku saat pengembangan kurikulum dilakukan. Misalnya ketika berlaku kurikulum bersifat nasional yang ditentukan oleh konsursium pendidikan, maka kurikulum yang dihasilkan belum mengarah pada pencapaian visi dan misi Unesa. Ketika peraturan tentang pengembangan kurikulum berlaku, maka kurikulum mulai ditata sesuai dengan arah dan prosedur yang benar.
Berdasarkan landasan historis tersebut maka proses pengembangan kurikulum perlu memperhatikan berbagai macam kelebihan dan kelemahan serta karakteristik kurikulum yang pernah dihasilkan dan dipergunakan. Hal ini perlu dijadikan landasan untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik dengan memperhatikan kondisi dan peraturan yang berlaku.
Pengembangan kurikulum saat ini harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.
Kebijakan Merdeka Belajar untuk sementara ini dijadikan solusi yang tepat dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Namun Nadiem (2020) menegaskan bahwa; ”Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT”. Artinya capaian belajar secara utuh menjadi orientasi dari kebijakan ini.
LANDASAN HUKUM
Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:
- Pancasila dan UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Gambar 1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.
Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved