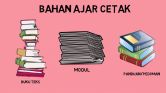Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Geografi Unesa
| Program Studi | : | S1 Pendidikan Geografi |
| Tanggal Berdiri | : | 11 Juli 1996 |
| Koordinator Program Studi | : | NUGROHO HARI PURNOMO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Misi
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran geografi yang inovatif dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global.
- Melaksanakan penelitian yang mengembangkan ilmu pendidikan geografi inovatif dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya aplikasi pendidikan geografi dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global.bidang
- Membangun kerjasama dengan berbagai komponen lembaga atau masyarakat lokal, nasional, dan internasional khususnya dalam bidang pendidikan geografi berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global
Tujuan
- Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran geografi yang inovatif dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global
- Terlaksananya penelitian yang mengembangkan ilmu pendidikan geografi inovatif dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global
- Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya aplikasi pendidikan geografi dengan pendekatan geografi dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global.bidang
- Terbangunnya kerjasama dan networking dengan berbagai lembaga atau masyarakat lokal, nasional, dan internasional khususnya dalam bidang pendidikan geografi berbasis IPTEKS dan geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan global
Nilai_dasar
- TANGKAAS REK (TANGguh, Kolaboratif, Adaptif, innovAtif, inkluSif, belajaR sEpanjang hayat, dan berbasis Kewirausahaan) 1. Tangguh: Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki daya juang. 2. Kolaboratif: mampu bekerja sama untuk menghasilkan ide atau menyelesaikan masalah. 3. Adaptif: mampu beradaptasi secara mandiri dan tanggung jawab terhadap perubahan melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus. 4. Inovatif: mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi atau ide baru dalam pemecahan masalah sesuai perkembangan zaman yang dilandasi jiwa kewirausahaan dan kaidah ilmiah. 5. Inklusif: mendukung seluruh individu tanpa memandang perbedaan, memfasilitasi keberhasilan semua orang, serta menghargai perbedaan pemikiran dan keberagaman. 6. Belajar sepanjang hayat: memiliki kesadaran akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, aktif menemukan cara-cara yang efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus. 7. Kewirausahaan: mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya dalam menghasilkan nilai tambah.
- Nilai dasar yang diacu mengikuti nilai-nilai dasar UNESA tertuang dalam PP Nomor: 37 Tahun 2022 tentang PTN-BH UNESA yaitu: 1. Pancasila, seluruh civitas akademika FISIPOL Unesa selalu memegang teguh Pancasila sebagai pandangan hidup, karakter, dan sendi kehidupan bangsa dan bermasyarakat 2. Ilmiah, seluruh civitas akademika FISIPOL Unesa selalu melakukan kegiatan dengan integritas tinggi dan bertanggung jawab secara keilmuan 3. Kewirausahaan, seluruh civitas akademika FISIPOL Unesa selalu berjiwa wirausaha dan mendorong upaya karakter berjuang dan berkorban dalam setiap proses. 4. Inklusif, seluruh civitas akademika FISIPOL Unesa selalu mendahulukan kepentingan umum, golongan inklusi dan lembaga dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Belajar sepanjang hayat, seluruh civitas akademika FISIPOL Unesa selalu berupaya belajar dan belajar untuk mendorong percepatan kualitas sumber daya manusia Indonesia Maju.
Visi
Mengembangkan keilmuan pendidikan geografi transformatif dalam konteks kajian kekotaan berbasis IPTEKS geospasial yang mendukung geo-edupreneur berwawasan globalCapaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Geografi
Pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan di sekolah, dengan kemampuan kerja yang dimiliki yaitu mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dalam bidang pendidikan geografi. Kompetensi pendukung :
- Mampu mengaplikasikan dinamika kebijakan pendidikan dan pembelajarannya
- Mampu memecahkan masalah pendidikan terkait dinamika kehidupan masyarakan dalam kontek geografi di suatu lingkungan wilayah tertentu
- Menguasai persoalan pendidikan dan pembelajaran dalam menjalankan peranan dan tanggung jawabnya di dalam kelas dan sekolah
- Praktisi Geografi
Pelaksana yang bertanggungjawab dalam pekerjaan mengumpulkan dan menganalisis data geografis. Kompetensi pendukung :
- Mampu mengumpulkan data geografis sumberdaya alam, kebencanaan, lingkungan, dan pengelolaan ruang
- Mampu menganalisis data geografis untuk sumberdaya alam, kebencanaan, lingkungan, dan pengelolaan ruang
- Mampu mengaplikasikan teknologi geografis untuk analisis sumberdaya alam, kebencanaan, lingkungan, dan pengelolaan ruang
- Wirausaha
Pelaksana yang bertanggungjawab dalam proses menjalankan usaha mandiri dalam sebuah tim kerja untuk mendapatkan keuntungan. ompetensi pendukung :
- Mampu melihat potensi dan melakukan analisis peluang usaha
- Mampu mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan banyak pihak untuk bersama menjalankan sebuah proses usaha
- Mampu mengambil keputusan secara cermat dan berani mengambil risiko yang kemungkinan terjadi dalam usaha
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Geografi 2024--2028
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720202196
ILMU WILAYAH
2.00
8720202080
KARTOGRAFI DASAR
2.00
8720202102
METEOROLOGI -KLIMATOLOGI
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
8720202120
PENGANTAR GEOGRAFI
2.00
8720202121
PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI
2.00
8720202203
DASAR PENDIDIKAN
2.00
8720202062
GEOLOGI UMUM
2.00
8720202197
GEOMORFOLOGI UMUM
2.00
8720202071
HIDROLOGI
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
8720203227
BENTANGLAHAN GEOGRAFI
3.00
8720202205
GEOGRAFI MANUSIA
2.00
8720202076
ILMU UKUR TANAH
2.00
8720202219
SIG DASAR
2.00
8720202192
TEORI BELAJAR
2.00
8720202021
DEMOGRAFI DAN GEOGRAFI PENDUDUK
2.00
8720202051
GEOGRAFI TANAH
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8720202198
EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
2.00
8720202030
GEOGRAFI DESA KOTA
2.00
8720202200
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8720203204
METODE PENELITIAN
3.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8720202167
STATISTIKA
2.00
8720203228
EKOLOGI & BIOGEOGRAFI
3.00
8720202199
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
8720202126
PENGINDERAAN JAUH DASAR
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720202032
GEOGRAFI EKONOMI & INDUSTRI
2.00
8720202034
GEOGRAFI KEBENCANAAN
2.00
8720202210
GEOGRAFI LINGKUNGAN
2.00
8720202039
GEOGRAFI PARIWISATA
2.00
8720202042
GEOGRAFI PERTANIAN
2.00
8720202044
GEOGRAFI POLITIK
2.00
8720202081
KARTOGRAFI TEMATIK
2.00
8720202222
MANAJEMEN KOTA
2.00
8720202110
OCEANOGRAFI
2.00
8720202208
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
2.00
8720202156
SIG ANALISIS LANJUT
2.00
8720202214
SIG TERAPAN
2.00
8720203229
ANALISIS WILAYAH
3.00
8720202048
GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA & ASIA TENGGARA
2.00
8720202212
GEOGRAFI SOSIAL BUDAYA
2.00
8720202050
GEOGRAFI SUMBERDAYA ALAM
2.00
8720202054
GEOGRAFI TRANSPORTASI
2.00
8720202058
GEOLOGI & GEOMORFOLOGI INDONESIA
2.00
8720202225
GEOMARITIM INDONESIA
2.00
8720202209
KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
8720202221
KOTA CERDAS
2.00
1000002212
PENGEMBANGAN KARIER
2.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (16 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (16 SKS)
- Paket Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (16 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
Matakuliah Asistensi Mengajar
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720204244
LINGKUNGAN PESERTA DIDIK (ASISTENSI MENGAJAR)
4.00
8720208241
PERENCANAAN PEMBELAJARAN (ASISTENSI MENGAJAR)
4.00
8720208243
PROSES PEMBELAJARAN (ASISTENSI MENGAJAR)
4.00
8720208242
PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (ASISTENSI MENGAJAR)
4.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720208239
ANALISIS DATA GEOINFORMASI
4.00
8720208240
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA GEOINFORMASI
4.00
8720208237
INVENTARISASI DATA GEOINFORMASI
4.00
8720208238
PENGOLAHAN DATA GEOINFORMASI
4.00
Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720204245
ANALISIS KEBUTUHAN PROYEK DESA
4.00
8720204247
IMPLEMENTASI PROGRAM PROYEK DESA
4.00
8720204246
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PROYEK DESA
4.00
8720204248
PENGEMBANGAN LAPORAN PROYEK DESA
4.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002051
PLP-ANALISIS KURIKULUM
2.00
1000002055
PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN
2.00
1000002049
PLP-MANAJEMEN SEKOLAH
2.00
1000003053
PLP-PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
3.00
1000002054
PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000004056
PLP-PRAKTIK MENGAJAR
4.00
1000002050
PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH
2.00
1000003052
PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
8720202040
GEOGRAFI PEMBANGUNAN WILAYAH
2.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
8720206163
SKRIPSI
6.00
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
8720202046
GEOGRAFI REGIONAL DUNIA
2.00
8720202215
PENGINDERAAN JAUH (PJ) TERAPAN
2.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720202196 | ILMU WILAYAH | 2.00 | |
| 8720202080 | KARTOGRAFI DASAR | 2.00 | |
| 8720202102 | METEOROLOGI -KLIMATOLOGI | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 8720202120 | PENGANTAR GEOGRAFI | 2.00 | |
| 8720202121 | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 2.00 | |
| 8720202203 | DASAR PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 8720202062 | GEOLOGI UMUM | 2.00 | |
| 8720202197 | GEOMORFOLOGI UMUM | 2.00 | |
| 8720202071 | HIDROLOGI | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 8720203227 | BENTANGLAHAN GEOGRAFI | 3.00 | |
| 8720202205 | GEOGRAFI MANUSIA | 2.00 | |
| 8720202076 | ILMU UKUR TANAH | 2.00 | |
| 8720202219 | SIG DASAR | 2.00 | |
| 8720202192 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
| 8720202021 | DEMOGRAFI DAN GEOGRAFI PENDUDUK | 2.00 | |
| 8720202051 | GEOGRAFI TANAH | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 8720202198 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8720202030 | GEOGRAFI DESA KOTA | 2.00 | |
| 8720202200 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
| 8720203204 | METODE PENELITIAN | 3.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 8720202167 | STATISTIKA | 2.00 | |
| 8720203228 | EKOLOGI & BIOGEOGRAFI | 3.00 | |
| 8720202199 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
| 8720202126 | PENGINDERAAN JAUH DASAR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720202032 | GEOGRAFI EKONOMI & INDUSTRI | 2.00 | |
| 8720202034 | GEOGRAFI KEBENCANAAN | 2.00 | |
| 8720202210 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 2.00 | |
| 8720202039 | GEOGRAFI PARIWISATA | 2.00 | |
| 8720202042 | GEOGRAFI PERTANIAN | 2.00 | |
| 8720202044 | GEOGRAFI POLITIK | 2.00 | |
| 8720202081 | KARTOGRAFI TEMATIK | 2.00 | |
| 8720202222 | MANAJEMEN KOTA | 2.00 | |
| 8720202110 | OCEANOGRAFI | 2.00 | |
| 8720202208 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8720202156 | SIG ANALISIS LANJUT | 2.00 | |
| 8720202214 | SIG TERAPAN | 2.00 | |
| 8720203229 | ANALISIS WILAYAH | 3.00 | |
| 8720202048 | GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA & ASIA TENGGARA | 2.00 | |
| 8720202212 | GEOGRAFI SOSIAL BUDAYA | 2.00 | |
| 8720202050 | GEOGRAFI SUMBERDAYA ALAM | 2.00 | |
| 8720202054 | GEOGRAFI TRANSPORTASI | 2.00 | |
| 8720202058 | GEOLOGI & GEOMORFOLOGI INDONESIA | 2.00 | |
| 8720202225 | GEOMARITIM INDONESIA | 2.00 | |
| 8720202209 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8720202221 | KOTA CERDAS | 2.00 | |
| 1000002212 | PENGEMBANGAN KARIER | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720204244 | LINGKUNGAN PESERTA DIDIK (ASISTENSI MENGAJAR) | 4.00 | |
| 8720208241 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN (ASISTENSI MENGAJAR) | 4.00 | |
| 8720208243 | PROSES PEMBELAJARAN (ASISTENSI MENGAJAR) | 4.00 | |
| 8720208242 | PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (ASISTENSI MENGAJAR) | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720208239 | ANALISIS DATA GEOINFORMASI | 4.00 | |
| 8720208240 | IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA GEOINFORMASI | 4.00 | |
| 8720208237 | INVENTARISASI DATA GEOINFORMASI | 4.00 | |
| 8720208238 | PENGOLAHAN DATA GEOINFORMASI | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720204245 | ANALISIS KEBUTUHAN PROYEK DESA | 4.00 | |
| 8720204247 | IMPLEMENTASI PROGRAM PROYEK DESA | 4.00 | |
| 8720204246 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PROYEK DESA | 4.00 | |
| 8720204248 | PENGEMBANGAN LAPORAN PROYEK DESA | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002051 | PLP-ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
| 1000002055 | PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 1000002049 | PLP-MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
| 1000003053 | PLP-PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 3.00 | |
| 1000002054 | PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 1000004056 | PLP-PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 | |
| 1000002050 | PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
| 1000003052 | PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 8720202040 | GEOGRAFI PEMBANGUNAN WILAYAH | 2.00 | |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 8720206163 | SKRIPSI | 6.00 | |
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 | |
| 8720202046 | GEOGRAFI REGIONAL DUNIA | 2.00 | |
| 8720202215 | PENGINDERAAN JAUH (PJ) TERAPAN | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengembangan (SOP) Kurikulum dokumen nomer PM-FISH.BPA-19 terbit tanggal 1 Februari 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, berikut prosedur untuk pengembangan kurikulum.
I. Pengembangan Kurikulum
- Pengembangan kurikulum program studi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1x dalam waktu 5 tahun.
- Tim pengembangan kurikulum harus ditetapkan melalui penerbitan SK / Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tim pengembangan kurikulum wajib melibatkan unsur-unsur terkait antara lain : Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Pengguna Lulusan.
Aktivitas pengembangan kurikulum meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya :
- Analisis kebutuhan dan studi kelayakan
- Studi banding
- Pelacakan alumni
- Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait
- Evaluasi kurikulum on-going
- Sanctioning
- Uji Publik
Keluaran dari pengembangan kurikulum adalah:
- Struktur kurikulum
- Deskripsi mata kuliah
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Keluaran dari pengembangan kurikulum harus melalui proses verifikasi oleh tim internal dan eksternal program studi dan melalui uji publik.
- Tim Internal terdiri dari para pakar kurikulum dalam 1 fakultas.
- Tim Eksternal terdiri dari para pakar kurikulum di luar PerguruanTinggi.
- Uji Publik yang dilakukan bersama dengan asosiasi profesi.
Keluaran dari pengembangan kurikulum setelah lolos dari proses verifikasi dan uji publik, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dekan.
II. Tinjauan Kurikulum
Tinjauan Kurikulum dilakukan setiap 2 tahun, untuk melihat pelaksanaan kurikulum selama 2 tahun berjalan dan dalam rangka mencari kesesuaian terhadap pencapaian kompetensi yang diinginkan. Keluaran kegiatan ini adalah adanya REVISI dari pelaksanaan kurikulum jika dibutuhkan.
III. Evaluasi kurikukum
Evaluasi Kurikulum dilakukan setiap 5 tahun, untuk melihat pelaksanaan kurikulum selama 5 tahun sebagai
Prosedur untuk pengembangan visi mengikuti pengembangan kurikulum. Hal ini karena prosesnya sama dengan pengembangan kurikulum. Data yang diperlukan juga relatif saling melengkapi antara visi dengan kurikulum. Selain itu efisiensi waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan.
Pegembangan kurikulum di S1 Pendidikan Geografi Unesa merujuk pada profil lulusan PT dan hasil tracer studi serta steakholder.
- Perkembangan keilmuan. Perkembangan keilmuan pendidikan dan geografi selalu didiskusikan setiap tahun di prodi. Penelusuran terhadap berita dan jurnal ilmiah dengan topik-topik terkait, juga dengan hasil diskusi pada pertemuan ilmiah tahunan profesi Ikatan Geograf Indonesia (IGI) dan Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI), menjadi sumber informasi perkembangan keilmuan.
- Perkembangan aplikasi keilmuan. Perkembangan aplikasi keilmuan pendidikan geografi sesuai profil lulusan S1 Pendidikan Geografi Unesa, banyak berkiprah di dunia pendidikan. Selain itu juga berkiprah sebagai wirausaha serta sebagian kecil menjalankan pada profesi geograf.
- Tracer study. Tracer study mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan yang selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas prodi.
- Kondisi alumni. Kondisi alumni merupakan kiprah alumni di dunia kerja meliputi pengetahuan, kemampuan dan kompetensi, yang di bangun ketika kuliah berdasarkan kondisi, pengalaman dan motivasi, pola/proses pengajaran dan pembelajaran, penelitian, praktikum, workshop, laboratorium, studio ataupun riset.
- Branchmarking. Branchmarking bermakna belajar dari pengalaman prodi lain sebagai tolak ukur pengalaman guna untuk membuat standar dalam memperbaiki proses di profi.
- Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan berdasarkan kajian perkembangan keilmuan, hasil kajian tracer study, dan branchmarking oleh tim kurikulum.
- Sancioning kurikulum. Sancioning kurikulum merupakan upaya pembahasan kurikulum yang dievaluasi dengan diskusi bersama pakar dan praktisi keilmuan yang relevan.
- Uji publik kurikulum. Uji publik merupakan upaya pembahasan kurikulum yang dievaluasi dengan diskusi bersama pemangku kepentingan yang relevan.
- Seminar kurikulum. Seminar kurikulum merupakan pemaparan dan didkusi kurikulum yang sudah direvitalisasi dengan masyarakat luas.
Analisis Kebutuhan dan Studi Kelayakan (Oktober - Desember 2024)
Sasaran Kurikulum Transformasi Pendidikan 2024
Peserta Didik.
- Menciptakan peserta didik yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan zaman.
- Mengembangkan kemampuan kolaborasi dan kerja sama antar peserta didik.
- Mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang adaptif terhadap perubahan.
- Membekali peserta didik dengan keterampilan inovatif dan kreatif.
- Memastikan semua peserta didik mendapat akses pendidikan inklusif tanpa diskriminasi.
- Menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat.
- Menanamkan jiwa kewirausahaan dalam diri peserta didik sejak dini.
Tenaga Pendidik
- Melatih tenaga pendidik untuk menerapkan metode pengajaran yang tangguh dan responsif.
- Mendorong kolaborasi antara tenaga pendidik dan stakeholder lainnya.
- Membekali tenaga pendidik dengan keterampilan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pedagogi.
- Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam metode pengajaran.
- Menyediakan pelatihan inklusif bagi tenaga pendidik.
- Memupuk budaya belajar sepanjang hayat dalam kalangan tenaga pendidik.
- Menginspirasi tenaga pendidik untuk mengajarkan kewirausahaan kepada peserta didik.
Institusi Pendidikan
- Mewujudkan institusi pendidikan yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan.
- Membangun lingkungan kolaboratif antara institusi pendidikan dan masyarakat.
- Mengembangkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.
- Mendorong inovasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan.
- Mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap semua kalangan.
- Menciptakan budaya belajar sepanjang hayat dalam lingkungan institusi pendidikan.
- Membangun program kewirausahaan yang terintegrasi dalam kurikulum institusi pendidikan.
Tujuan Kurikulum Transformasi Pendidikan 2024
- Meningkatkan Daya Tahan dan Ketangguhan. Membentuk karakter peserta didik yang kuat dan resilient dalam menghadapi berbagai tantangan.
- Mengembangkan Kemampuan Kolaborasi. Mendorong kerja sama tim, komunikasi efektif, dan kemampuan kolaboratif antar peserta didik dan tenaga pendidik.
- Memperkuat Adaptabilitas. Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi.
- Mendorong Inovasi dan Kreativitas. Menginspirasi peserta didik dan tenaga pendidik untuk berinovasi dalam setiap aspek pendidikan.
- Mewujudkan Pendidikan Inklusif. Memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang.
- Menumbuhkan Semangat Belajar Sepanjang Hayat. Menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik dan tenaga pendidik untuk terus belajar dan berkembang.
- Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan. enanamkan nilai-nilai kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha pada peserta didik.
Karakteristik Kurikulum Transformasi Pendidikan 2024
- Tangguh. Kurikulum dirancang untuk membentuk karakter peserta didik yang resilient dan mampu menghadapi tantangan global.
- Kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek dan kerja tim menjadi fokus utama dalam metode pengajaran.
- Adaptif. Kurikulum yang fleksibel dan dinamis, mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
- Inovatif. Mendorong pendekatan pembelajaran yang kreatif dan pemanfaatan teknologi terbaru dalam proses pendidikan.
- Inklusif. Menjamin akses pendidikan bagi semua peserta didik dengan berbagai latar belakang.
- Belajar Sepanjang Hayat. Menanamkan semangat dan budaya belajar yang berkelanjutan dalam diri peserta didik dan tenaga pendidik.
- Kewirausahaan. Integrasi keterampilan kewirausahaan dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler.
Tracer Study / Pelacakan Alumni (Januari 2025)
Tracer Study / Pelacakan Alumni dan survai masyarakat dilakuan lewat https://tracerstudy.unesa.ac.id/. Instrumen yang menjadi tujuan survai adalah terkait visi dan kurikulum sebagai berikut.
- capaian kompetensi,
- capaian keselarasan luaran,
- orientasi kurikulum,
- kepuasan layanan,
- pemahaman visi,
- kesesuaian visi dengan kurikulum, penelitian, serta perkembangan di masyarakat.
Sasaran survai dan jumlahnya adalah sebagai berikut.
- pemangku kepentingan (5),
- pengguna lulusan (5),
- alumni (10),
- masyarakat (5),
- mahasiswa (5).
Analisis Kesesuaian Kompetensi
Kesesuaian kompetensi yang dikembangkan selama pendidikan dengan bidang yang ditekuni setelah selesai pendidikan cenderung meningkat pada relevnasi tinggi dan menurun pada relevasn sedang dan rendah selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dikembangkan memiliki kesesuaian antara pendidikan dengan bidang yang ditekuni setelah lulus. Hal ini menunjukkan bahwa banyak bidang yang dapat dilakukan berdasarkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan.
Tabel Relevansi Pekerjaan dengan Pendidikan
| Tahun | Relevansi Bidang Kerja (%) | ||
| - | Tinggi | Sedang | Rendah |
| 2024 | 82 | 11 | 7 |
| 2023 | 76 | 13 | 11 |
| 2022 | 75 | 12 | 13 |
Analisis Tingkat Ketenagakerjaan
Keselarasan vertikal (kesesuaian bidang kerja) pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kesesuaian bidang kerja tidak selaras. Dialog dengan lulusan baru memberikan informasi bahwa lowongan pekerjaan yang selaras dengan bidangnya saat ini sangat terbatas. Hal ini dapat dipahami dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pengangkatan tenaga pendidik dengan regulasi yang cukup ketat seperti syarat profesional maupun tidak bolehnya tenaga honorer. Untuk keselarasan horisontal (kesesuaian tingkat pekerjaan) dominan pada tingkat yang sama dan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diperoleh dominan selevel dengan tingkat pekerjaan yang diperoleh.
Tabel Keselarasan Vertikal dan Horisontal
| Tahun | Keselarasan Vertikal (kesesuaian bidang kerja) | Keselarasan Horisontal (kesesuaian tingkat pekerjaan) | ||||||||
| Selaras | Tidak Selaras | Setingkat Lebih Tinggi | Tingkat yang Sama | Setingkat Lebih Rendah | ||||||
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | |
| 2024 | 22 | 39.29 | 34 | 60.71 | 7 | 12.73 | 43 | 78.18 | 5 | 9.09 |
| 2023 | 28 | 65.12 | 15 | 34.88 | 5 | 12.50 | 30 | 75.00 | 5 | 12.50 |
| 2022 | ||||||||||
Analisis Umpan Balik untuk Pengembangan Kurikulum
Umpan balik lulusan terhadap kurikulum dominan menyarankan tentang penguatan penguasaan teknologi. Teknologi geospasial merupakan bidang yang perlu diperdalam selama proses pendidikan. Selanjutnya adalah penguatan pada bidang pendidikan. Kemampuan berkomunikasi dan pemahaman terhadap peserta didik sebagai upaya penguasaan kelas merupakan usulan yang perlu diperkuat. Selanjutnya penguatan pada bidang lingkungan dan sosial.
Tabel Umpan balik orientasi masa depan keilmuan yang perlu dikembangkan dalam kurikulum
| Pendidikan | Sosial | Teknologi | Lingkungan |
| 25% | 13% | 43% | 19% |
Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna
Tingkat kepuasan pengguna cenderung dominan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari variabel etika, kinerja, kerja tim, komunikasi, penggunaan teknologi, dan upaya pengembangan diri. Keadaan tersebut sangat potensial untuk berkontribusi terhadap karier. Hal ini menunjukkan selama pendidikan juga mengembangkan karakter. Namun emikian lembaga perlu terus meningkatkan sampai capaian yang optimal.
Tabel Kepuasan Pengguna Lulusan
| No. | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | |||
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
| 1 | Etika berperilaku | 71.9 | 28.1 | 0.0 | 0 |
| 2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 74.6 | 25.4 | 0.0 | 0 |
| 3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 76.4 | 23.6 | 0.0 | 0 |
| 4 | Kemampuan berkomunikasi | 66.2 | 33.8 | 0.0 | 0 |
| 5 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 61.3 | 38.7 | 0.0 | 0 |
| 6 | Upaya pengembangan diri | 68.7 | 31.3 | 0.0 | 0 |
Analisis Pemahaman Visi
Pengembangan visi mengikuti yang ada di fakultas dan universitas. Pengembangan visi tersebut merupakan evaluasi dari visi sebelumnya. Secara umum visi baru tidak beda banyak dengan visi baru. Hal ini karena persoalan masa mendatang cukup dipahami dari periode pengembangan seb
| No | Uraian | Tingkat Pemahaman (%) | ||
| Paham | Kurang paham | Tidak Paham | ||
| 1 | Informasi visi dari media digital | |||
| 2 | Informasi visi dari media cetak | |||
| 3 | Informasi visi dari kurikulum | |||
| 4 | Informasi visi dari publikasi penelitan | |||
| 5 | Informasi visi dari pengabdian kepada masyarakat | |||
| 6 | ||||
Analisis Pengembangan visi
Pengembangan visi mengikuti yang ada di fakultas dan universitas. Pengembangan visi tersebut merupakan evaluasi dari visi sebelumnya. Secara umum visi baru tidak beda banyak dengan visi baru. Hal ini karena persoalan masa mendatang cukup dipahami dari periode pengembangan sebalumnya. Survai komponen dan implementasi visi dilakukan terhadap 30 responden yang terdiri dari pemangku kepentingan, alumni, mahasiswa, dan masyarakat serta dosen.
Tabel Urgrnsi komponen dan implementasi visi
| No. | Komponen Visi | Tingkat Urgensi (%) | |||
| Sangat urgen | Urgen | Cukup urgen | Kurang urgen | ||
| 1 | Visi pendidikan geografi transformatif | 82 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Visi kajian kekotaan | 76 | 23 | 1 | 0 |
| 3 | Visi IPTEKS geospasial | 78 | 21 | 1 | 0 |
| 4 | Visi geo edupranur | 71 | 28 | 1 | 0 |
| 5 | Visi daya saing global | 68 | 30 | 2 | 0 |
| 6 | Visi memenuhi tantangan masa depan pendidikan geografi | 84 | 14 | 2 | 0 |
| 7 | Pembenahan implementasi visi dalam tridarma | 89 | 11 | 0 | 0 |
Benchmarking
Beradasrkan umpan balik dalam tracerstudy, penguatan penguasaan teknologi geospasial bagi lulusa, maka dilakukan benchmarking ke S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 6 Februari 2025. Selain itu juga ke forum Perkumpulan Peminat Pembelajaran Geografi Indonesia (P3GI) di Universitas Negeri Yogyakarta pada 9-10 Mei 2025.
Dalam benchmarking ke S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kesempatan tersebut dibahas hal-hal sebagai berikut.
- Membahas kompetensi dan keterampilan yang diharapkan dari lulusan setelah memprogram matakuliah kelompok teknologi geospasial mencakup pengukuran apakah kompetensi yang diajarkan dalam kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau standar di bidang tersebut.
- Materi Pembelajaran kelompok teknologi geospasial yang diajarkan mencakup apakah materi tersebut up-to-date, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta seberapa dalam materi tersebut diajarkan.
- metode atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum, seperti apakah mengutamakan pembelajaran aktif, diskusi kelompok, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau bentuk lain yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
- menilai apakah fasilitas dan sumber daya yang ada (misalnya laboratorium, ruang kelas, bahan ajar, perangkat teknologi) mendukung implementasi kelompok matakuliah teknologi geospasial yang efektif, juga memastikan bahwa kurikulum dapat diterapkan dengan optimal dan memberikan pengalaman belajar yang maksimal.
- Sejauh mana stakeholder eksternal, seperti industri, pengguna lulusan, atau profesional, terlibat dalam pengembangan kelompok matakuliah teknologi geospasial sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan pasar kerja serta perkembangan profesional di bidang tertentu.
Foto Benchmarking di UGM 6 Februari 2025
Dalam benchmarking ke forum Perkumpulan Peminat Pembelajaran Geografi Indonesia (P3GI) di Universitas Negeri Yogyakarta dibahas terkait arah pengembangan kurikulum dan pembelajaran geografi bertujuan menjadikan geografi sebagai mata pelajaran yang kontekstual, relevan, dan transformatif, sehingga mampu mencetak generasi yang sadar ruang, peduli lingkungan, dan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi dinamika dunia. Penjabarannya sebagai berikut.
1. Berbasis Kompetensi dan Literasi
- Kompetensi abad 21: Kurikulum geografi diarahkan untuk mengembangkan kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
- Literasi Geospasial: Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi berbasis lokasi.
- Literasi lingkungan dan global: Menumbuhkan kesadaran terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Kontekstual dan Berbasis Kearifan Lokal
- Materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat.
- Mendorong pemanfaatan sumber daya lokal sebagai media pembelajaran.
- Mengintegrasikan kearifan lokal dalam memahami hubungan manusia dan lingkungan.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Data Geospasial
- Mengintegrasikan teknologi seperti GIS (Geographic Information System), remote sensing, dan digital mapping dalam pembelajaran.
- Pemanfaatan peta digital, aplikasi berbasis lokasi, dan data spasial real-time sebagai sumber belajar.
4. Pendekatan Interdisipliner dan Tematik
- Menghubungkan geografi dengan ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, biologi, dan sejarah.
- Menggunakan pendekatan tematik, terutama dalam membahas isu-isu global dan regional seperti urbanisasi, bencana alam, dan migrasi.
5. Pengembangan Karakter dan Kepedulian Sosial-Lingkungan
- Menumbuhkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan dampak tindakan manusia terhadap bumi.
- Mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya.
6. Pembelajaran Aktif dan Inkuiri Geografis
- Mengutamakan model pembelajaran aktif, seperti project-based learning, problem-based learning, dan inquiry-based learning.
- Siswa didorong untuk melakukan observasi, pengumpulan data lapangan, analisis spasial, dan pemecahan masalah nyata.
7. Adaptif terhadap Perubahan Kurikulum Nasional
- Disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum Merdeka.
- Mendorong fleksibilitas guru dan sekolah dalam merancang modul ajar sesuai kebutuhan peserta didik.
Foto Benchmarking di forum P3GI UNY 9 Mei 2025
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Surabaya
Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum, Profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO) yang meliputi pengetahuan, keterampilan (Umum dan Khusus) dan sikap.
LATAR BELAKANG
Landasas filosofi
- Perenialisme menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Aliran ini menyatakan sebuah kebenaran tidak akan berubah selamanya.
- Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- Rekonstruksionisme menekankan pentingnya pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk menghasilkan kehidupan modern di masa mendatang. Hasil belajar sangat diperhatikan oleh rekonstruksionisme dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dari masing-masing peserta didik.
- Eksistensialisme berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah membantu setiap individu untuk mampu mewujudkan dirinya sebagai manusia.
- Romantik naturalisme mendasarkan pada suatu fakta bahwa perkembangan seorang anak adalah spontan dan alamiah. Seorang anak tidak digambarkan sebagai papan yang kosong, tetapi sebagai individu yang memiliki perasaan dan bakat tertentu.
- Eksperimentalisme menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi sepanjang hayat. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik adalah merupakan kontruksi pemahaman dari hasil interaksinya dengan berbagai sumber belajar dan dialog dengan teman sebaya.
Filosofi pendidikan geografi membawa kesadaran tentang pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hubungan antara manusia dan lingkungannya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitarnya.
Beberapa prinsip filosofis yang mendasari pendidikan geografi :
Keterhubungan: Pendidikan geografi mengajarkan tentang keterkaitan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana fenomena geografis seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam memengaruhi kehidupan manusia, serta bagaimana manusia mempengaruhi dan merespons lingkungan mereka.
Keberagaman: Geografi menghargai keragaman budaya, sosial, dan ekologis di seluruh dunia. Pendidikan geografi mengajarkan penghormatan terhadap beragam budaya dan identitas, serta pentingnya menjaga keberagaman lingkungan alam.
Kritis dan Kreatif: Pendidikan geografi mendorong siswa untuk berpikir secara kritis tentang tantangan dan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi global. Ini melibatkan mempromosikan pemikiran kritis dan solusi kreatif untuk masalah seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Keterlibatan dan Tanggung Jawab: Pendidikan geografi tidak hanya tentang memahami dunia, tetapi juga tentang mengambil tindakan untuk meningkatkannya. Ini melibatkan memotivasi siswa untuk menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan mempromosikan keadilan sosial di seluruh dunia.
Kebijaksanaan dan Keberlanjutan: Filosofi pendidikan geografi menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan memahami dampak jangka panjang dari keputusan manusia terhadap lingkungan dan mendorong tindakan yang memperhatikan keberlanjutan.
Melalui pendidikan geografi yang berbasis filosofi ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dunia yang mereka tinggali dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan masyarakat global.
Landasan sosiologis
Landasan sosiologis memberikan arah pengembangan kurikulum ini untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan sosial budaya yang kuat serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya dimanapun tempatnya berada. Pada dasarnya, setiap lingkungan masyarakat selalu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Karakteristik ini membentuk kearifan lokal dan budaya daerah yang berbeda-beda. Interaksi antar kelompok masyarakat dan individu mendorong terjadinya perkembangan nilai ini. Perkembangan nilai budaya dan pengetahuan yang ada dalam masyarakat tersebut adalah satu hasil olah pikir dan logika serta interaksi dari masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut.
Landasan sosiologis pendidikan geografi mengacu pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pemahaman dan interaksi manusia terhadap lingkungan geografis mereka. Ini mencakup studi tentang bagaimana faktor-faktor seperti budaya, struktur sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi cara manusia memahami, menggunakan, dan memanfaatkan ruang geografis.
Beberapa konsep kunci dalam landasan sosiologis pendidikan geografi meliputi:
Budaya dan Identitas: Pendidikan geografi mempertimbangkan bagaimana budaya dan identitas masyarakat memengaruhi persepsi dan penggunaan ruang geografis. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana budaya lokal membentuk pola penggunaan lahan, struktur permukiman, dan pola migrasi.
Struktur Sosial dan Ketimpangan: Landasan sosiologis pendidikan geografi juga menyoroti dampak struktur sosial, termasuk ketimpangan ekonomi dan akses ke sumber daya, terhadap distribusi spasial kekayaan, kesempatan, dan kualitas hidup. Ini dapat memperluas pemahaman tentang pola geografis ketimpangan dan keadilan sosial.
Globalisasi dan Perubahan Sosial: Pendidikan geografi mempertimbangkan bagaimana proses globalisasi memengaruhi interaksi sosial dan pola spasial di seluruh dunia. Ini mencakup studi tentang mobilitas manusia, perdagangan, dan arus informasi yang mempengaruhi transformasi geografis seperti urbanisasi, suburbanisasi, dan gentrifikasi.
Keterlibatan Masyarakat: Landasan sosiologis pendidikan geografi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pemahaman dan penyelesaian masalah geografis. Ini dapat melibatkan keterlibatan komunitas dalam perencanaan lingkungan, pelestarian alam, dan pengelolaan risiko bencana.
Perspektif Kritis: Sosiologi mempromosikan pemikiran kritis tentang struktur sosial dan ketimpangan kekuasaan. Dalam konteks pendidikan geografi, ini melibatkan analisis kritis terhadap hubungan antara struktur sosial dan pola geografis, serta pengembangan pemahaman yang kritis tentang isu-isu sosial dan lingkungan.
Melalui landasan sosiologis ini, pendidikan geografi berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dengan lingkungan mereka dan memotivasi tindakan yang berkelanjutan dan inklusif dalam mengatasi tantangan geografis global.
Landasan historis
Geografi di wilayah Indonesia sudah diajarkan sejak jaman pendudukan Belanda dan Jepang, dengan nama ilmu bumi (Sandy, 1988; 18). Di dalam kurikulum pendidikan kolonial pada waktu itu, diutamakan penguasaan bahasa Belanda dan hal-hal mengenai Negeri Belanda. Misalnya dalam pengajaran ilmu bumi, anak-anak bumi putra harus menghapal kota-kota kecil yang ada di negeri Belanda (Tilaar, 1995)
Pasca kemerdekaan, mata pelajaran ilmu bumi masih tetap dilanjutkan.Mata pelajaran tersebut sudah diajarkan sejak Kurikulum (Rencana Pelajaran) 1947. Pada waktu itu fungsi mata pelajaran ilmu bumi disesajarkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi pada akhirnya kedua mata pelajaran tersebut memiliki “nasib” yang berbeda. Bahasa Indonesia dibuat lembaga pembinaan Bahasa Indonesia dan diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Untuk ilmu bumi tidak dibuatkan lembaga pembinaan cinta tanah air Indonesia, dan mengalami pasang surut di bidang pendidikan formal.
Pada tahun 1951, untuk meningkatkan mutu guru di sekolah-sekolah menengah dalam ilmu bumi, didirikan kursus-kursus B-I dan kemudian B-II. (Naskah Akademik Kurikulum Geografi, Puskurbuk, 2010). Waktu kursus selama dua tahun dan mata kursusnya membahas unsur-unsur ilmu bumi dan membahas tentang wilayah serta kondisi beberapa negara. Hal yang agak aneh adalah tidak ada pokok bahasan tentang geografi Indonesia. Selain itu tidak pernah ada diskusi yang mendalam tentang esensi geografi yang perlu diajarkan di Indonesia. Di kurikulum sekolah, Ilmu Bumi diajarkan sampai tahun 1980-an, selanjutnya pada Kurikulum 1984 sudah menggunakan nama Geografi.
Tahun 1950 ilmu bumi di perguruan tinggi diajarkan pada Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan nama Jurusan Ilmu Bumi. Pada tahun 1963, jurusan ilmu bumi memisahkan diri menjadi Fakultas Geografi UGM. Sementara itu sekitar akhir tahun 60-an, atas prakarsa Jenderal Gatot Subroto dan Jenderal Prof. Dr. Mustopo didirikan Jurusan Geografi di Universitas Padjajaran Bandung. Selanjutnya oleh rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro, Jurusan Geografi di UNPAD dipindahkan ke Universitas Indonesia (UI) di Jakarta.
Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya yang sebelumnya adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), pada awalnya juga merupakan perkembangan dari kursus-kursus B-I dan kemudian B-II ilmu bumi. Perkembangan kurikulum ilmu bumi di IKIP Surabaya saat itu, tidak lepas dari adanya interaksi antara jurusan sejenis di berbagai IKIP di Indonesia. Komunikasi antar jurusan sejenis menjadi awal dari perkembangan kurikulum sampai saat ini.
Sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi, perkembangan kurikulum Jurusan Pendidikan Geografi, mengikuti perkembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia. Perkembangan kurikulum tersebut mengikuti dasar sebagai berikut ini.
- Kurikulum yang berbasis pada Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (UU no. 22 Tahun 1961, Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 , Perpres no. 14 Tahun 1965)
- Kurikulum diatur Pemerintah ( UU no. 2 tahun 1989, PP no. 60 Tahun 1999 )
- Pergeseran paradigma ke konsep KBK, Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi (UU no. 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kepmendiknas no. 232/U/2000, dan perubahan kurikulum inti di Kepmendiknas no 045/U/2002)
- Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri ( PP no. 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 4, PP 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 2)
- Dikembangkan berbasis kompetensi (PP no. 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 1)
- Minimum mengandung 5 elemen kompetensi( PP no. 17 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3)
- Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI (Perpres No. 08 tahun 2012)
- Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI (UU PT No. 12 Tahun 2012 pasal 29)
Kurikulum pendidikan geografi di persekolahan mulai disadari sebagai bagian penting dalam membangun dan mewariskan cinta tanah air dengan memahami seluruh wilayah Republik Indonesia. Potensi sumberdaya dan bencana di Indonesia merupakan bagian yang perlu dipahami oleh setiap warga negara. Hal ini mendorong pemerintah mengambil kebijakan mulai kurikulum 2013 mata pelajaran geografi dapat dimasukkan pada kelompok Ilmu Pengetahuan Alam, sebagai mata pelajaran lintas minat. Hal tersebut merevisi kurikulum 1994 sampai dengan kurikulum KTSP (2006), dimana geografi di tingkat sekolah menengah atas masuk dalam mata pelajaran kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sehingga hanya dipelajari anak-anak IPS. Terlebih lagi hamper semua jurusan Geosains di perguruan tinggi sebagian besar merupakan jurusan IPA.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka orientasi pengembangun kurikulum di Jurusan Pendidikan Geografi FISH Unesa mengacu pada kebijakan pengembangan kurikulum di kementerian pendidikan dan perkembangan orientasi ilmu geografi di persekolahan dengan tetap melihat perkembangan ilmu geografi di masyarakat lokal dan global. Pimpinan Unesa sekitar tahun 2012 telah menyusun pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan pedoman kementerian pendidikan, Pedoman tersebut juga terus berkembang mengikuti kebijakan kementerian. Pedoman tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum di Jurusan Pendidikan Geografi Unesa.
Awal perkembangan kurikulum di Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian utama, yaitu ilmu pendidikan, geografi fisik, dan geografi manusia. Perkembangan selanjutnya di sekitar awal tahun 2000-an, geografi teknik mulai diperkuat. Perubahan paradigma keilmuan geografi selanjutnya adalah ke arah geografi terpadu. Perkembangan kurikulum tersebut dilakukan oleh staf dosen di Jurusan Pendidikan Geografi Unesa yang didasarkan pada perkembangan kurikulum nasional pendidikan geografi yang mengikuti perkembangan ilmu geografi di Indonesia.
Semenjak tahun 2012, kurikulum Jurusan S1 Pendidikan Geografi Unesa telah telah dikembangkan menggunakan kurikulum kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam KKNI memperjelas profil lulusan pendidikan geografi, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat. Profil lulusa terdiri dari 3 berikut ini.
- Pendidik bidang geografi
- Profesional bidang pemetaan geografi
- Wirausaha bidang pendidikan dan pemetaan geografi
Konsekwensi dari hal tersebut adalah penguatan kurikulum di bidang pendidikan dan geografi teknik yang berorientasi geografi terpadu. Pengembangan orientasi kurikulum tersebut telah melalui proses sansioning dan uji public kurikulum di tahun 2014.
Perkembangan arah kurikulum di tahun 2020 yang dikenal sebagai merdeka belajar kampus merdeka, mendorong S1 Pendidikan Geografi Unesa untuk meninjau kembali kurikulum yang sudah diterapkan. Orientasi materi masih pada kajian geografi terpadu dengan penguatan pendidikan geografi dan sains informasi geografis. Pada restrukturisasi kurikulum ini, menguatkan orientasi kurikulum KKNI yang berbasis outcame dalam wadah merdeka belajar. Wadah merdeka belajar yang dikembangkan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengkaji geografi secara multidisiplin dan memberikan pilihan kebebasan mahasiswa beraktivitas. Kajian multidisiplin memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan untuk mengkaji terapan geografi yang dapat mendukung kompetensi inti bidang studinya.
Programe Education Objective (PEO)
- Mampu memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pembelajaran pendidikan geografi, menganalisis bentang lahan, melakukan survey dan pemetaan, mengaplikasikan teknologi geografi, dan kewirausahaan (PEO-1).
- Peduli, ramah lingkungan dan tanggap bencana, serta pemahaman tentang tanggung jawab profesional dan etis (PEO-2).
- Individu dengan sikap belajar sepanjang hayat melalui studi pascasarjana, kegiatan pelatihan, penelitian baik secara nasional maupun internasional (PEO-3).
Programe Learning Outcame (PLO)
| 1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
| 2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan |
| 3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan |
| 4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. |
| 5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat guna penyelesaian masalah pendidikan dalam pembelajaran geografi transformatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni |
| 6 | Mampu memperoleh, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi tentang lingkungan kependidikan, peserta didik, kurikulum, materi, perencanaan, model, evaluasi, dan refleksi pembelajaran dalam kajian pendidikan dan pembelajaran geogarfi |
| 7 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat guna penyelesaian masalah wilayah dalam konteks ruang berdasarkan pendekatan geografi terpadu |
| 8 | Mampu memperoleh, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi geosfer dengan menggunakan teknologi geospasial dalam kajian geografi terpadu yang mendukung keberlanjutan wilayah |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved